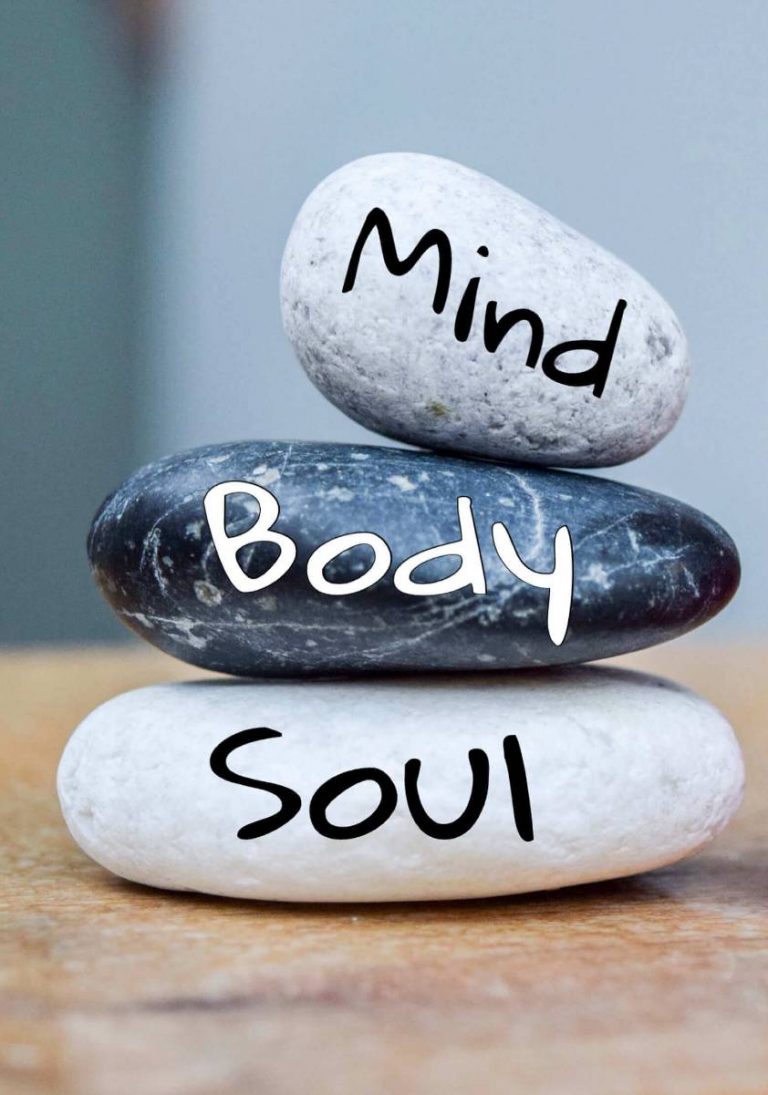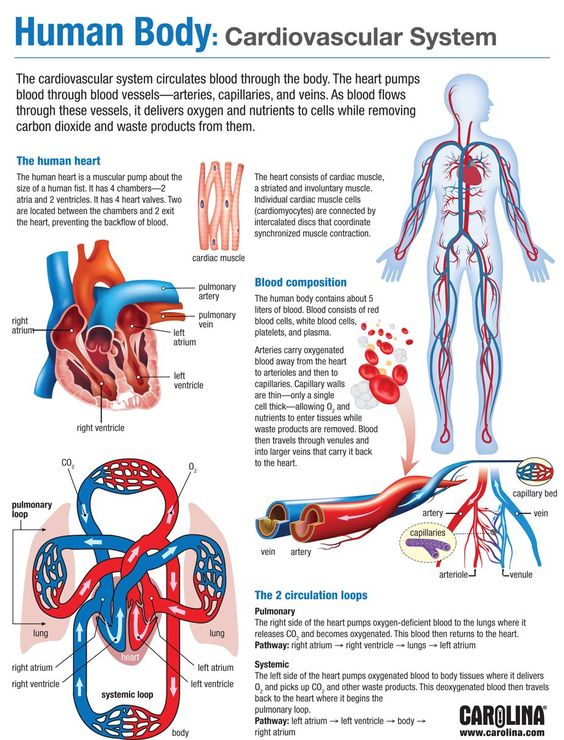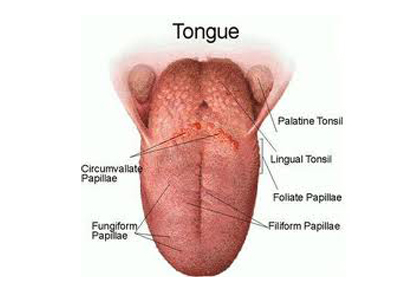TIRANI & NAIVITAS BIROKRASI I
1. MELAMPAUI KEWENANGAN
Merambah Bidang Yang Bukan Menjadi Kompetensinya
Birokrasi juga terlampau jauh mencampuri urusan redaksional kemasan dan petunjuk cara pakai obat tradisional, yang bukan merupakan bidangnya, dengan akibat, bahasa Indonesia menjadi rusak. Tanpa menguasai tatabahasa dan kosa kata yang baik dan benar, mereka secara arogan dan sekenanya mengganti kata atau kalimat yang diusulkan oleh pendaftar. Akibat begitu alergi terhadap istilah akan “obat” dan “penyakit” maka kedua kata ini dilarang dipergunakan, dengan akibat, makna kalimatnya berubah. Bahasa gaul lisan sehari-hari dipergunakan untuk mewakili bahasa tulisan formal yang memunyai kaidah tersendiri.
Andil Birokrasi Dalam Merusak Bahasa Nasional
Akibatnya, kalimat yang terbentuk, bisa tanpa mengandung subyek atau obyek kalimat. Kalimat “Tuangkan isi sebungkus obat ini” diganti menjadi “Tuangkan isi sebungkus ini” karena kata “obat” dicoret oleh mereka. Kata “penyakit” pada padanan kata “penderita penyakit kanker” juga wajib dihapus, sehingga perkataan yang terbentuk adalah “penderita kanker.” Padahal kata “kanker” berarti “kepiting.” Dengan demikian, terciptalah makna “penderita kepiting.” “Penderita penyakit maag” diubah menjadi “penderita maag” yang berarti “penderita lambung.” Alhasil, “lambung” menjadi nama penyakit.
Kebijakan Yang Tidak Konsisten Dan Konsekuen
Apa yang mengherankan adalah mereka sendiri memakai istilah akan “obat” pada nama instansinya seperti Subdirektorat Obat Tradisional atau Direktorat Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetik. Jika mengikuti pola pikir dan gaya bahasa mereka sendiri, maka instansinya seharusnya disebut Subdit Tradisional, dan Direktorat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Kosmetika. Apa jadinya jika dalam petunjuk cara pemakaian obat terdapat anjuran atau larangan agar “penderita harus menghindari asap obat nyamuk?” Akan sangat janggal jika diubah menjadi “pengguna harus menghindari asap nyamuk.”
Merasa Berhak Menikmati Kewenangan Instansi Lain
Hanya karena alergi terhadap kata “penyakit” dilaranglah kata ini digunakan pada kemasan dan petunjuk pemakaian obat tradisional, maka secara logis namun satir, kalimat “hindari obat lain” akan diubah menjadi “hindari lain.” Mungkin kalimat “Penyakit masyarakat dapat meningkatkan penyakit kelamin” akan diubah menjadi “Masyarakat dapat meningkatkan kelamin.” Kewenangan atas ketentuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sejatinya menjadi porsi dari Pusat Bahasa. Instansi lain seyogyanya menggunakan jasa Pusat Bahasa, bukan menciptakan sendiri logika bahasa dan tatabahasanya.
Melarang Sekadar Asal Melarang Saja, Tanpa Diberikan Alternatif
Di masyarakat awam terdapat istilah “Obat Dewa,” namun istilah ini tidak ada kaitannya dengan dewa atau dewi, melainkan berarti bahwa satu macam obat dapat dipergunakan untuk mengobati banyak macam penyakit. Istilah ini berasal dari penerjemahan istilah Xian Yao dari bahasa Mandarin. Jika secara harfiah diterjemahkan, memang menjadi “Obat Dewa.” Xian berarti dewa dan Yao berarti obat. Akan tetapi konotasi dalam bahasa Mandarin bukanlah obat gaib yang berasal dari Kahyangan, melainkan obat yang serbaguna. Istilah ini dilarang dipergunakan oleh birokrasi, namun tidak diberikan alternatif padanannya.
Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari
Kerancuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan saja terjadi pada instansi tingkat bawah, namun juga merebak di instansi tingkat atas. Kata “Ibu Negara” yang pada masa lampau berarti “ibu kota,” ternyata digunakan untuk menyebut istri Kepala Negara. Pada zaman Belanda sampai awal kemerdekaan, dalam bahasa Melayu Hindia Belanda, “ibu kota” disebut sebagai “ibu negara” atau “kota raja.” Istri Kepala Negara seyogyanya disebut sebagai Wanita Utama atau Ibu Utama yang sepadan dengan sebutan “First Lady” dalam bahasa Inggris. Entah apa gerangan yang diurus oleh Pusat Bahasa Indonesia?
Pusat Bahasa Bungkam, Bahasa Indonesia Gonjang-ganjing
Ada lagi istilah yang sangat aneh yakni penggunaan istilah preman yang dikenakan pada penjahat. Padahal di masa lalu preman berarti polisi reserse berpakaian sipil yang tugasnya justru adalah menjadi lawan dari penjahat. Kata ini berasal dari bahasa Belanda yakni freiman yang berarti manusia bebas yang dalam konteks ini berarti orang sipil atau orang yang berpakaian sipil. Hanya dalam tempo kira-kira tiga puluh tahun, arti katanya menjadi amat bertolak belakang. Belum lagi istilah “mutakhir” yang diartikan sebagai “terkini,” padahal dalam bahasa aslinya yakni bahasa Arab, artinya adalah terkebelakang.
Terlalu Banyak Yang Hendak Diurus Mengakibatkan Blunder
Terlalu banyak yang hendak ditata mengakibatkan tidak ada yang tertata, malah menimbulkan kerancuan yang sangat karut marut karena keanehan dan kelucuannya. Sudah waktunya silang sengkarut ini harus segera diakhiri demi kecerahan masa depan per-jamu-an di Indonesia. Penyakit utama birokrasi kita adalah merasa dirinya sebagai superbody sehingga berwenang menetapkan aturan atau syarat apapun, baik yang logis maupun tidak. Banyak persyaratan yang sejatinya menjadi kewenangan instansi lain, namun juga diberlakukan, sehingga pelanggan harus menyediakan persyaratan tersebut berulang kali.
Kendala Bagi Obat Tradisional Menjadi Tuan Di Rumah Sendiri
Jika pola pemakaian “kacamata kuda” semacam itu oleh birokrasi, tidak “dibasmi” melalui suatu reformasi birokrasi yang mendasar, maka selamanya Indonesia tidak akan menjadi tuan di rumah sendiri dalam hal pengobatan tradisional, dengan segala dampak yang menyertainya. Akibat lebih mudahnya mengedarkan obat tradisional impor ketimbang memeroleh izin di dalam memroduksi sendiri dan mengedarkannya, maka tidaklah mengherankan jika kini sudah terlalu banyak obat tradisional dan suplemen makanan asing yang membanjiri pasar obat tradisional Indonesia, yang berarti pemborosan devisa.
Tunggu bagian kedua >>>>>
Sumber:
Buku Kembali Ke Alam (Back to Nature)
oleh Dr. Aggi Tjetje & Dr. Some
(Suatu Tinjauan Mendalam Akan: Kiprah dan Sumbangsih Serta Pengabdian Pengobatan Tradisional Dalam Pembangunan Nasional)